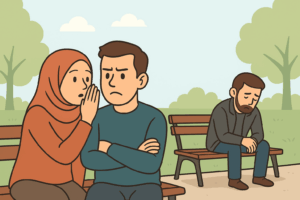Feodalisme di Pesantren? Meluruskan Stigma Lewat Kacamata Adab dan Khidmah
Pemandangan santri yang berjalan menunduk saat berpapasan dengan guru (kiai), mencium tangan dengan takzim, hingga bekerja bakti membangun atau membersihkan lingkungan pesantren seringkali memicu perdebatan di ruang publik. Bagi sebagian kalangan yang melihat dari luar, tradisi ini bisa disalahartikan sebagai bentuk feodalisme—sebuah sistem hierarkis yang menempatkan penguasa di puncak dan rakyat jelata sebagai pelayan tanpa pamrih. Tuduhan ini menyamakan kiai dengan seorang tuan tanah dan santri sebagai budak yang dieksploitasi.
Namun, apakah benar demikian? Apakah tradisi luhur yang telah mengakar ratusan tahun di pondok pesantren ini sesederhana label feodalisme? Untuk menjawabnya, kita perlu membongkar kesalahpahaman ini dengan memahami esensi dari adab (etika) dan khidmah (pengabdian) dalam tradisi keilmuan Islam.
Membedakan Feodalisme dan Kultur Pesantren
Mari kita definisikan apa itu feodalisme. Feodalisme adalah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang dominan di Eropa abad pertengahan. Intinya adalah hubungan antara tuan (lord) dan bawahan (vassal) yang didasarkan pada kepemilikan tanah. Tuan tanah memberikan lahan kepada bawahannya sebagai imbalan atas layanan militer atau kerja paksa. Relasi ini bersifat eksploitatif dan didasarkan pada kekuasaan material.
Sekarang, mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi di pondok pesantren. Relasi antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kepemilikan tanah atau kekuasaan duniawi, melainkan di atas fondasi transmisi ilmu dan keberkahan.
Posisi guru dalam Islam begitu mulia, dalam kitab Jami’ al-Ahadits (Maktabah Turoth, hal. 391) Rasulullah ﷺ menegaskan dalam sebuah hadis:
أكْرِمُوا العُلَمَاءَ فإنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ أكرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ الله وَرَسُولَهُ
Artinya: “Hendaklah kamu semua memuliakan para ulama (guru) karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka, siapa memuliakan mereka, berarti memuliakan Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Al-Khatib Al-Baghdadi).
Hadis ini memberikan landasan teologis yang kokoh. Memuliakan guru bukanlah bentuk perbudakan, melainkan sebuah tindakan ibadah karena mereka adalah “pewaris para nabi”. Di pesantren, seorang santri diajarkan bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ia harus memuliakan sumber ilmu tersebut. Ini bukan ketaatan buta, melainkan sebuah metode pendidikan spiritual. Santri meyakini bahwa guru adalah wasilah atau perantara yang menyambungkan sanad keilmuan mereka hingga kepada Rasulullah ﷺ.

Lalu, bagaimana dengan aktivitas seperti membantu pembangunan (ngecor), membersihkan lingkungan, atau melayani kebutuhan guru?
Dalam tradisi pesantren, aktivitas ini disebut khidmah. Khidmah adalah bentuk pengabdian tulus seorang murid sebagai wujud terima kasih dan cara untuk mendapatkan ridha serta keberkahan dari gurunya. Para santri melakukannya secara sukarela dengan harapan ilmunya menjadi lebih berkah.
Bagaimana dengan gestur menunduk atau duduk bersimpuh di hadapan guru yang disebut-sebut seperti feodalisme di pesantren?
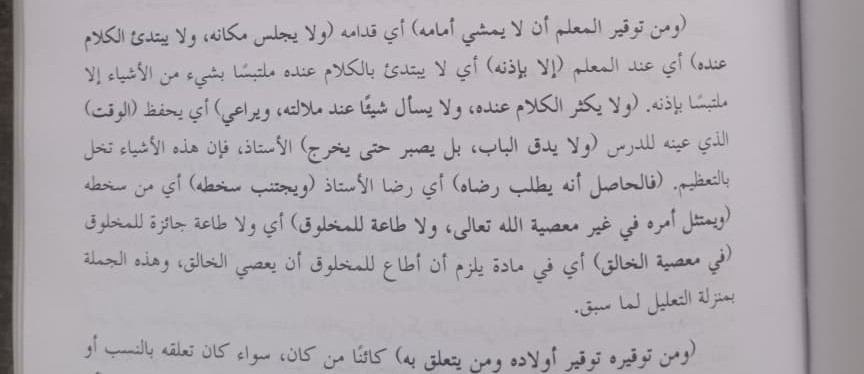
Cetakan Dar Al Kutub Al Islamiyah
Syekh az-Zarnuji dalam kitab ta’limul muta’allim (Cet. Dar Al-Kutub al-Islamiyah: Jakarta, hal. 43) menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari adab memuliakan seorang guru. Beberapa adab yang ditekankan antara lain tidak berjalan di depan guru, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai pembicaraan kecuali atas izinnya.
Puncak dari pemahaman ini terangkum dalam perkataan agung Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dinukil oleh Syekh az-Zarnuji dalam ta’limul muta’allim (Cet. Dar Al-Kutub al-Islamiyah: Jakarta, hal. 41) sebagaimana berikut:
انا عبد من علمني ولو حرفا واحدا إن شاء، إن شاء باع، إن شاء أعتق، إن شاء استرق
“Aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan ilmu kepadaku, meskipun hanya satu huruf. Kalau mau, dia bisa menjual. Kalau mau, dia bisa membebaskan. Kalau mau, dia bisa memperbudak.”
Ungkapan ini bukanlah pengakuan perbudakan harfiah, melainkan metafora puncak kerendahan hati seorang murid.
Pesantren: Benteng Pendidikan Karakter Bangsa

Jika kultur adab dan khidmah ini disalahpahami sebagai feodalisme, maka sebagian masyarakat yang menilai pandangan tersebut, belum memahami adab dan khidmah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana hadis di atas. Pondok pesantren bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga tempat untuk menempa adab dan karakter. Di saat banyak lembaga pendidikan modern hanya fokus pada kecerdasan intelektual, pesantren tetap teguh mempertahankan prinsip bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu.
Seorang santri tidak hanya diajarkan cara membaca kitab, tetapi juga cara memuliakan kitab itu sendiri, seperti tidak memegangnya kecuali dalam keadaan suci atau tidak meletakkan benda lain di atasnya. Mereka belajar memuliakan teman seperjuangan dan menyerahkan pilihan cabang ilmu yang harus dipelajari kepada guru yang lebih berpengalaman. Para santri di masa lalu berhasil meraih tujuannya karena mereka menyerahkan urusan pendidikannya kepada guru, tidak seperti pelajar masa kini yang seringkali memilih sendiri sehingga tidak mencapai tujuannya.
Inilah kekayaan pendidikan pesantren yang sering luput dari perhatian. Pesantren mendidik santri untuk menjadi pribadi yang tahu cara berterima kasih, menghormati orang yang lebih tua dan berilmu, serta memiliki kerendahan hati. Kualitas-kualitas inilah yang semakin langka di tengah masyarakat modern yang cenderung individualistis dan pragmatis.
Oleh karena itu, melabeli tradisi luhur ini sebagai “feodalisme” adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya. Apa yang terlihat seperti penindasan dari luar sesungguhnya adalah metode pendidikan jiwa yang mendalam. Itu bukanlah feodalisme, melainkan sebuah ekosistem spiritual di mana ilmu, adab, dan keberkahan menyatu untuk membentuk manusia yang utuh—berilmu sekaligus berakhlak mulia.
Referensi
Suyuthi, I.J. Jami’ al-Ahadits (CD: Maktabah Turoth). Hal. 391
Zarnuji, S.(2007). Ta’limul Muta’allim. Jakarta: Dar Al Kutub Islamiyah hal. 41
Penulis: Alfin Haidar Ali